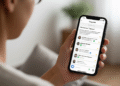Sebuah kabar menyeruak dari Washington D.C., membawa serta wacana yang menggelitik rasa kebangsaan sekaligus nalar kemanusiaan kita. Yehuda Kaploun, sosok yang baru dikonfirmasi sebagai Utusan Khusus AS untuk Memantau dan Memerangi Antisemitisme, menyuarakan keinginannya untuk “mengubah” buku ajar di Indonesia. Alasannya klasik: menekan bibit kebencian.
Redaksi mencatat, wacana ini muncul dengan premis data yang goyah—menyebut Indonesia memiliki 350 juta Muslim, sebuah angka yang secara statistik meleset jauh dari fakta demografi kita. Namun, marilah kita kesampingkan sejenak kekeliruan data tersebut. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, lebih filosofis, dan lebih krusial untuk didiskusikan daripada sekadar angka: yakni tentang ilusi social engineering (rekayasa sosial) di era keterbukaan dan makna sejati dari memanusiakan manusia.
Kampung Global yang “Rumpi”
Dunia hari ini bukan lagi dunia tahun 1940-an di mana propaganda bisa disuntikkan secara tunggal melalui corong radio atau dikte buku sekolah. Kita hidup di tengah 8 miliar manusia yang terkoneksi dalam sebuah “kampung global yang rumpi”.
Gagasan bahwa mengubah satu paragraf dalam buku teks di sekolah dasar di pelosok Jawa akan serta-merta mengubah cara pandang generasi muda terhadap geopolitik global adalah sebuah kenaifan di era digital. Anak-anak hari ini belajar dari realitas yang mereka lihat, bukan hanya dari teks yang mereka baca.
Dinding-dinding kelas telah runtuh digantikan oleh layar gawai. Ketika sebuah narasi dipaksakan—namun bertabrakan dengan fakta visual yang viral di media sosial secara real-time—maka narasi itu akan “mati angin”. Propaganda, sehalus apa pun, akan luruh ketika dihadapkan pada kenyataan telanjang tentang ketidakadilan yang terekam kamera netizen. Upaya membersihkan nama baik atau menanamkan simpati tidak bisa lagi dilakukan lewat revisi kurikulum, melainkan lewat konsistensi perilaku di panggung dunia.
Monopoli Trauma dan Standar Ganda
Poin kedua yang menjadi catatan kritis Redaksi adalah tentang cara kita memandang tragedi. Istilah “antisemitisme” dan trauma sejarah yang melekat padanya, seringkali didengungkan sedemikian rupa seolah menjadi satu-satunya standar penderitaan yang harus diakui dunia.
Di sini letak kerancuan logikanya. Menolak kebencian adalah kewajiban moral setiap manusia beradab. Namun, menjadikan satu jenis tragedi sebagai “kiblat” penderitaan, sembari menutup mata pada tragedi kemanusiaan (holokaus dalam bentuk lain) yang terjadi hari ini di belahan bumi lain, adalah bentuk standar ganda yang mencederai rasa keadilan.
Holokaus adalah tragedi kemanusiaan, titik. Genosida di Gaza adalah tragedi kemanusiaan, titik. Pembantaian etnis di manapun adalah tragedi kemanusiaan. Tidak boleh ada hierarki dalam penderitaan. Masalah sesungguhnya bukanlah pada label etnisnya—Yahudi, Arab, Asia, atau Eropa—melainkan pada ketidakmampuan mendasar manusia untuk saling memanusiakan. Kebencian tidak lahir dari buku ajar; ia lahir dari hilangnya empati dan pengingkaran terhadap hak hidup orang lain yang berbeda.
Jalan Keluar: Keteladanan, Bukan Intervensi
Maka, jika tujuannya adalah menghapus kebencian dan menumbuhkan penerimaan, intervensi kurikulum asing bukanlah jawabannya. Itu adalah langkah top-down yang justru berpotensi memicu resistensi dan sentimen anti-asing yang kontraproduktif.
Cara paling efektif—dan mungkin satu-satunya cara yang tersisa di abad ini—adalah dengan memberi contoh (lead by example).
Jika dunia ingin melihat wajah yang ramah, tunjukkanlah wajah yang ramah itu dalam kebijakan, dalam perlakuan terhadap warga sipil, dan dalam penghormatan terhadap nyawa manusia tanpa pandang bulu. Buktikan bahwa etnis Yahudi, sebagaimana etnis lainnya di muka bumi ini, berdiri setara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.
Ketika laku lampah memanusiakan sesama itu terwujud nyata, buku ajar tak perlu diubah paksa. Rasa hormat dan simpati akan tumbuh secara organik di hati para siswa, melampaui apa yang tertulis dalam tinta kurikulum manapun.
Dunia sedang menonton, dan dunia tidak butuh editor buku. Dunia butuh teladan kemanusiaan.