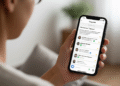Di Lhokseumawe, Aceh, pada malam yang basah setelah banjir, sebuah insiden kembali menguji nalar berbangsa kita. Konvoi bantuan kemanusiaan dicegat, bendera bulan bintang diturunkan, dan kekerasan fisik tak terhindarkan.
Di permukaan, ini tampak seperti episode klasik: aparat keamanan versus separatis. Namun, jika kita berani melihat lebih dalam—melampaui laporan situasi harian dan metrik keberhasilan operasi—kita akan menemukan pola sejarah yang berulang dengan mengerikan karena terus diabaikan.
Insiden 25 Desember 2025 ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah gejala dari penyakit lama yang tak kunjung sembuh di tubuh republik ini: ketidakadilan yang meradang menjadi perlawanan.
Benang Merah “Luka Keadilan”
Sejarah Indonesia mencatat bahwa pemberontakan jarang sekali dimulai dari ideologi murni. Dari ujung barat hingga timur, tarikan garis sejarah membuktikan bahwa perlawanan lahir dari “perut yang lapar” dan “harga diri yang diinjak”.
Lihatlah Aceh di masa lalu. Gerakan yang kita labeli separatisme itu tidak tumbuh semata-mata karena keinginan mendirikan negara agama. Ia membesar di tahun 1970-an, ketika ladang gas Arun ditemukan dan ribuan triliun rupiah kekayaan alam disedot ke pusat, sementara rakyat di sekitar kilang tetap miskin. Kekecewaan ekonomi itulah penyakit aslinya. Ketika Jakarta menjawabnya dengan Operasi Militer (DOM), kekecewaan itu bermutasi menjadi dendam darah.
Hari ini, pola itu berulang: warga kecewa karena bantuan banjir lambat (ketidakadilan penanganan), bendera putih yang mereka kibarkan ‘cuma’ dianggap noise, bukan voice, lalu mereka mengibarkan bendera lama sebagai simbol protes. Simbol itu hanyalah teriakan; akarnya adalah rasa diabaikan.
Lihatlah Papua. Di balik label OPM atau KKB, terdapat luka batin akibat kekayaan alam yang dikeruk tanpa menyisakan kesejahteraan setara, ditambah dengan pendegradasian rasial yang membuat mereka merasa tidak “dimanusiakan” dalam sistem sosial kita. Pembangunan infrastruktur fisik hanyalah obat pereda nyeri yang memadamkan gejala ketertinggalan, namun tidak menyentuh sel kanker ketidakadilan itu.
Bahkan mundur ke era PRRI/Permesta di tahun 1950-an, pemberontakan para perwira di Sumatera dan Sulawesi adalah koreksi atas pembangunan yang Jawa-sentris. Ketika tuntutan pemerataan (koreksi) dianggap makar, senjata pun bicara.
Jebakan Sindrom “KPI”
Sayangnya, respons negara sering kali terjebak pada sindrom “KPI” (Key Performance Indicator) yang dangkal.
Dalam kasus Aceh kemarin, keberhasilan mungkin diukur dari narasi: “Massa bubar”, “Bendera turun”, “Senjata disita”. Secara metrik keamanan, itu adalah sukses.
Namun secara penyelesaian masalah bangsa, itu adalah kegagalan total. Mengapa? Karena rasa lapar dan kecewa korban banjir belum terobati.
Besok lusa, bendera itu—atau simbol perlawanan lainnya—akan naik lagi karena “penyakitnya” (ketidakadilan distribusi) masih ada.
Aparat di lapangan, yang juga adalah anak-anak bangsa, sering kali hanya menjalankan tugas dalam koridor komando yang kaku: “Jaga NKRI Harga Mati”.
Tanpa panduan kemanusiaan yang spesifik di daerah bencana, kelelahan fisik dan mental membuat mereka merespons simbol perlawanan warga sebagai ancaman militer, bukan sebagai jeritan putus asa.
Video yang beredar memperlihatkan ketegangan antara aparat dan warga, popor senjata yang melayang, dan bendera bulan bintang yang disita. Namun, di balik riuh rendah saling tuding soal “separatisme” versus “pelanggaran HAM”, ada satu kenyataan senyap yang luput kita bicarakan: Kelelahan Kolektif.
Mari kita lepaskan sejenak kacamata politik dan mengenakan kacamata kemanusiaan dalam melihat peristiwa ini.
Di satu sisi, kita melihat prajurit TNI. Mereka adalah anak-anak bangsa yang didoktrin untuk patuh pada komando. Tanpa instruksi spesifik yang memandu detail gerak-gerik kemanusiaan di lapangan, naluri dasar mereka adalah menjaga kedaulatan—”NKRI Harga Mati”. Ketika kelelahan fisik mendera pasca-operasi bencana, dan dihadapkan pada provokasi simbolik, batas kesabaran itu runtuh.
Reaksi represif yang muncul mungkin bukan karena kebencian, melainkan karena absennya panduan teknis untuk “mematikan” mode tempur dan menyalakan mode pengayom di situasi krisis.
Di sisi lain, kita melihat rakyat jelata yang terluka. Bukan hanya oleh bencana alam, tapi oleh rasa ketidakadilan yang menumpuk. Ketika bantuan terlambat dan perut lapar, logika “menang atau kalah” tidak lagi berlaku.
Pengibaran bendera atau simbol perlawanan bukanlah strategi militer untuk makar; itu adalah jeritan putus asa. Itu adalah bentuk perlawanan dari mereka yang merasa tidak punya pilihan lain untuk didengar. Mereka melawan bukan karena yakin akan menang, tapi karena diam bukan lagi pilihan.
Kesalahan terbesar kita hari ini adalah melabeli salah satu pihak sebagai “Lawan”.
Tidak ada lawan di Aceh hari ini. Tidak ada musuh negara di tenda pengungsian. Yang ada hanyalah sesama saudara sebangsa yang sama-sama lelah fisik, lelah mental, dan mulai kehilangan harapan.
Konflik ini tidak akan selesai dengan membakar bendera “lawan”, karena sesungguhnya tidak ada bendera yang perlu dimusuhi selain bendera kemiskinan dan ketidakadilan. Konflik ini hanya bisa diredam jika para pemangku kepentingan (stakeholders) mampu hadir bukan sekadar sebagai komandan yang memberi perintah makro, tapi sebagai teladan yang ikut mengerjakan instruksinya.
Ketika keteladanan kecil itu hadir, rasa curiga akan luruh.
Tidak Ada Musuh, Hanya Kelelahan
Sudah saatnya kita mengubah kacamata. Tidak ada “lawan” di Aceh, di Papua, atau di daerah konflik lainnya. Yang ada adalah sesama saudara yang sedang lelah. Lelah berharap akan keadilan dan pemerataan.
Rakyat lelah menanti keadilan dan bantuan yang tak kunjung tiba. Aparat lelah menjaga stabilitas tanpa dukungan kebijakan yang menyentuh akar masalah. Statemen-statemen tanpa empati dan logika keluar dari para pejabat ikut memperburuk situasi. Ketika dua pihak yang kelelahan ini berbenturan, yang terjadi adalah tragedi, bukan kemenangan salah satu pihak.
Gerakan perlawanan di Indonesia sejatinya adalah “Language of the Unheard”—bahasa mereka yang tidak didengar. Mereka berteriak minta adil soal ekonomi, pusat mengirim pasukan. Mereka berteriak minta dihormati hak asasinya, pusat mengirim beton dan aspal.
Menyalakan Dapur Rakyat
Merawat Indonesia tidak bisa lagi hanya dengan narasi “NKRI Harga Mati” yang buta tuli. Narasi itu harus dibarengi dengan “Keadilan Harga Mati”. Tanpa keadilan, persatuan hanya menjadi sangkar besi yang membelenggu, bukan rumah yang nyaman untuk berteduh.
Kita tidak bisa memadamkan api separatisme dengan menangkan dan membakar bendera yang dikibarkan. Kita hanya bisa memadamkannya dengan “menyalakan dapur rakyat”. Pastikan bantuan banjir tiba tepat waktu, pastikan kue pembangunan terbagi rata, dan pastikan setiap warga negara—apa pun etnis dan latar belakangnya—merasa dimanusiakan oleh negaranya sendiri.
Hanya dengan itulah, bendera perlawanan akan turun dengan sendirinya, digantikan oleh rasa memiliki yang tulus terhadap Republik ini.