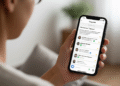KITA hanyalah bayang, saling berbaur, bersilangan, berhimpitan dan akan ditimpa oleh bayang-bayang yang lain, hilang kemudian dilupakan. Kisah kehidupan di muka bumi akan terus bergulir, datang dan pergi, silih berganti. Dan ketika tiba saatnya salah satu di antara kita ditakdirkan bertemu kereta kencana lebih dulu, para sahabat tercabik duka yang dalam, kehilangan.
***
Aku tahu kau akan berangkat, meski tidak tahu kapan. Tapi sejak Ais berkabar di penghujung tahun 2023 tentang dirimu yang kembali terbaring di rumah sakit, entah mengapa, ada semacam gelombang kecemasan menghantam diriku. Meski begitu, kulambungkan doa terbaik ke langit demi kesembuhanmu. Setelahnya, aku berusaha menepis perasaan kacau itu. Tapi seperti ada sesuatu yang “memintaku” berangkat ke Makassar. Firasatku, yang seringkali salah, kali ini seakan benar. Maka kuputuskan untuk mengabadikan percakapan kita terakhir kali pada tanggal 3 Januari pukul 10.27 wita, via sambungan telepon. Pukul 12.22 wita Ais mengirim kabar bahwa kau telah pamit, melepas pegangan dari tali kehidupan. Rekaman percakapan itu masih kusimpan. Aku anggap bahwa kau tidak benar benar pergi, tapi masih hidup bersama kami, para sahabatmu yang selalu mencandaimu, merindukanmu.
Sulur-sulur kenangan semasa bersamamu pun kembali terurai. Banyak cerita tersimpan di danau pengetahuan yang selalu kau rawat dengan sungguh, di jalan Kelinci, di utara kota Makassar.
Sebab usiaku terpaut jauh lebih muda dari usiamu, setiap kali kau bentangkan kisah masa lalumu yang penuh warna, maka kupilih lebih banyak mendengar, membuka hati dan berenang di lautan hikmah, membaca perjalanan hidupmu.
Aku ikut tersenyum saat kau tuturkan roman picisanmu pertama kali kau bertemu Maryam Simamora —gadis Batak-Sidrap— yang begitu kau cintai, yang memberimu tiga mata hati. Aku pun bisa merasakan apa yang terkandung dalam tarikan napasmu yang berat saat kau terkenang teduh wajahnya, merdu suaranya. Kau benar-benar kehilangan dirinya. Mataku berkaca kaca ketika kau bercerita tentang anak-anakmu dan peristiwa yang mengikuti perjalanan kisah hidup mereka. Juga cucu-cucumu, Indah dan Butet. (O ya, seingatku kau pernah menyebut anakmu Ais sebagai anak bandel yang sulit diatur, tapi kukira kau telah melebarkan senyum setelah sekian tahun atas hasil didikanmu ia bermetamorfosa menjadi seorang lelaki kuat, cerdas dan tentu saja mewarisi ketampananmu).
Danau pengetahuan berupa perpustakaan kecil itu kau tata dan kau rawat dengan cinta sebab katamu dengan cara itulah kau mengenang ibumu yang selalu kau ulang-ulang ceritakan. Di matamu, beliau adalah seorang pembelajar yang tidak pernah berhenti membaca selain pandai menulis surat dalam bahasa Arab. Di antara buku buku, majalah, dan tumpukan koran, kau membayangkan ibumu tetap ada di sana, menatapmu. Kadang aku melihatmu seperti anak kecil yang rindu belaian sang bunda meski saat itu kau telah melampaui usia ibumu sendiri. Cintamu yang begitu besar sehingga perpustakaanmu kau namai dengan nama ibumu menjadi “Usthask Kita”. Kata “Usthask” sendiri berarti “Ummi Sitti Khadijah Syam Kaba”. Bola matamu menyala menemukan nama itu. Dengan bersemangat kau meminta pendapatku. Segera kuiyakan sebab ini soal kecintaan terhadap ibu. Tak mungkinlah kubantah meski kurasa sedikit aneh kependekannya. Untuk melengkapinya, kau pun memintaku membuat logonya. Segera kucorat-coret di kertas, dan beberapa hari kemudian jadilah plang-nya. (Adapun kata “Kita” yang mengikutinya, entahlah, saya tidak ingat lagi apa artinya).
***
Anis, sahabatku, setiap kali kita lepas berbincang, dan kau biarkan aku duduk menekuri satu buku bacaan yang kau pilihkan dari rak bukumu, tentu tidak kau tahu bahwa aku terkadang mencuri pandang, diam diam melihatmu larut bersama irama mesin ketik tuamu, menulis sajak-sajak. Di usia senjamu, tak kau biarkan dirimu diiris pedang waktu tanpa berkarya dan berbagi. Betapa kedamaian dan kesejukan berlimpah melengkapi detak-detik waktu yang memanjang entah dimana batasnya.
Ketika kau selesai, kepalamu mengangguk-angguk seperti berusaha membaca ulang diksi yang kau temukan. Tidak jarang mesin ketik tuamu itu berderit kencang karena kau menarik paksa kertas yang menempel. Kau lalu menggantinya dengan yang baru dan dengan cepat kau ketik lagi untuk merevisi draf sajak sebelumnya. Lagi, kau mengangguk-angguk dan kau akhiri dengan senyuman puas.
Memerah langit di ufuk barat
Sebaris kalimat meriak di telaga senyap
Kita berjalan menyusur langit yang lindap
Membaca setiap isyaratKetika malam menurunkan kelam
Tarian kunang-kunang mencipta keharuan
Pelita yang engkau pasang
Menyingkap tabir kerinduan *1
Sebuah kejutan kau ciptakan! Kau sodori aku secarik kertas yang baru saja kau petik dari rasa terdalammu.
“Ini khusus untuk Muhary,” katamu sembari tersenyum. Lalu kubaca dengan saksama. Terbayang perjalanan kita berdua menyusuri toko-toko buku, menduplikasi kitab langka, ngopi di warung-warung tua, sekadar berbincang tentang kota Makassar yang juga beranjak tua, sahabatsahabat seperjuanganmu yang telah lebih dulu pergi, tentang rencanamu mengabadikan sajak-sajakmu menjadi sebuah buku.
“Terima kasih, Pak Anis. Ini indah sekali. Ternyata Pak Anis pandai memotret,” jawabku menangapi sajakmu sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku.
“Ya dulu memang aku suka memotret.” Ha-ha kubiarkan kau mengalir bersama pikiranmu sendiri. Tidak apa. Itulah keuntungan bersahabat dengan yang lebih tua. Kita yang muda sepatutnya belajar lebih banyak sabar dan memaklumi. “Masih kusimpan kameraku, tapi ya tidak terpakai lagi. Kapan kapan kutunjukkan padamu.”
Setelahnya kita akan mengawang dengan suguhan secangkir kopi diimbuh musik klasik macam Bach, Mozart, atau Tchaikovsky. Seakan kau tidak pernah ingin mengakhiri setiap pertemuan. Kau selalu bahagia setiap kali sahabatmu berkunjung.
Kau petik cahaya di langit senja
Beragam warna bermain di mata
Kau jaring bunyi di hari yang sepi
Beragam suara di bisikan hati
Menyulam kala sunyiMembayang di malam hari
Pejalan yang tak pernah mati
Mengurai simpul setiap hari
Melewati tebing masa silam, berganti
Menyanyikan rindu pada puisi *2
Anis Kaba, sahabatku. Aku tulis catatan ini sekadar untuk mengenang pertemuan dan perjalanan kita bersama di masa dahulu. Terima kasih atas setiap kata, sehimpun kisah, dan hikmah yang kau berikan. Engkau adalah persona yang berhati permata, seorang lelaki yang sangat mencintai keluarganya. Beban di pundakmu terus kau usung meski tidak jarang kau merasa letih.
Menjelang akhir hayatmu, kau memutuskan untuk menyisih ke tepi sepi, mendaras sebanyak mungkin kitab suci alquran, mendawamkan dzikrullah, yang membuatmu damai se damai-damainya. Engkau tahu petualanganmu di dunia fana ini akan berganti ke perjalanan selanjutnya. Engkau telah menandai dirimu dengan karya yang telah dibaca banyak orang: Nyanyian Alam, Mantera Bumi, dan Kembara Angin dan Cahaya. Engkau telah menyimpan setangkai mawar di hati kami semua.
Pertemuan kita pertama kali di gedung RRI pada sebuah perhelatan seniman adalah pertemuan yang tak terelakkan. Awal dari petualangan untuk saling mengenali satu sama lain, saling membuka pintu gerbang kisah masing-masing, berbagi manis pahit kehidupan ini.
Selamat jalan, Kakakku. Tidurlah engkau bersama udara. Tidurlah di keluasan taman sorgawi dengan tenang. Dalam haribaanNya yang penuh kasih.
***
Kita hanyalah bayang, saling berbaur, bersilangan, berhimpitan dan akan ditimpa oleh bayang-bayang yang lain, hilang kemudian dilupakan. Kisah kehidupan di muka bumi akan terus bergulir, datang dan pergi, silih berganti. Dan kita pun menanti, siapa di antara kita yang ditakdirkan menyisih ke tepi sepi saat lonceng kereta kencana berbunyi, meninggalkan para sahabat tercabik duka yang dalam, kehilangan…
waktu lonceng berbunyi
percakapan merendah, kita kembali
menanti-nanti
kau berbisik: siapa lagi akan tiba
siapa lagi menjemputmu berangkat berdukadi ruangan ini kita gaib dalam gema.
di luar malam hari
mengendap, kekal dalam rahasia
kita pun setia memulai percakapan kembali
seakan abadi, menanti-nanti lonceng berbunyi. *3
Tambora, Nusa Tenggara Barat, 02/2024
Muhary Wahyu Nurba
—–
Keterangan:
1. Puisi Pelita Malam, Anis Kaba, 2002
2. Puisi Meditasi, Anis Kaba, 2006
3. Puisi Dalam Sakit, Sapardi Djoko Damono, 1967