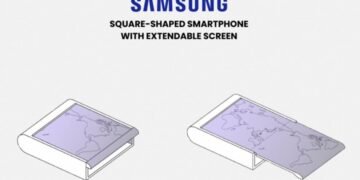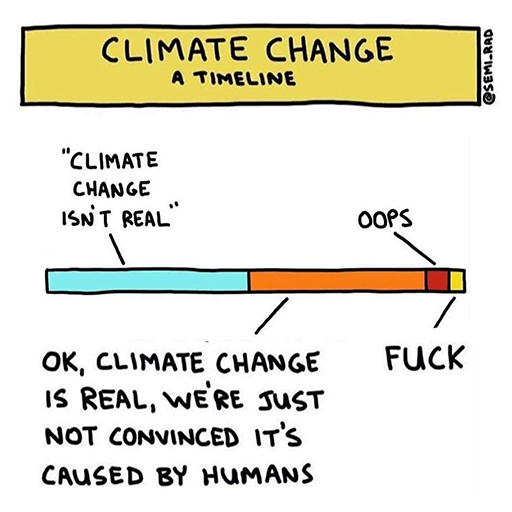Guru bahasa Indonesia semasa SMA sulit terlupakan, pak Rahmat Banjar. Arti namanya keren, kasih sayang yang berjejer rapi. Beliau disukai murid-muridnya, mungkin karena satu dari dua jam pelajaran dipakai bercanda dengan kami.
Kurikulum CBSA (cara belajar siswa aktif) mengharuskan kelas membaca sendiri bagian penjelasan sebelum masuk ke soal dan latihan. Awalnya pak Rahmat Banjar juga begitu, hingga suatu kali di deret pertama dari tiga deret kolom meja dan kursi, seorang kawan kedapatan asyik membaca stensilan Enny Arrow, diselipkan dalam buku cetak bahasa Indonesia, anak 90an biasanya tahu.
Sejak itu pembagian bangku di kelas kami menurut jenis kelamin, daerah stensilan ditandai sebagai daerah rawan untuk perempuan. Tidak mau tertipu dengan bacaan lain yang kami sisipkan ke dalam buku, sekelas tidak boleh lagi membaca sendiri. Satu persatu bergiliran ke depan membaca lembar demi lembar. Akhirnya tiba giliran Pudin. Pak Rahmat Banjar mengamati keringat sebesar jagung keluar dari dahi Pudin yang berdiri di depan kelas. Kecepatannya membaca satu kalimat sudah sehalaman untuk waktu yang sama bila kami yang membaca.
Makin gagap Pudin, makin usil pak Rahmat Banjar mengageti Pudin. Gagap lalu gagu, kemudian mengulang lagi membaca dari awal. Anehnya saat diminta mengaji Qur’an Pudin lancar tak terbendung.
Dua semester Pudin menderita dan cuma pak Banjar yang menyadari bahwa gagap Pudin berkurang drastis, keringat sebesar jagung tidak jatuh lagi dari dahinya. Asal tidak dikageti Pudin bisa membaca selancar kami. Bagi kami hiburan, bagi pak Banjar pendidikan privat. Pudin gagap membaca dan kami gagap pahami pendidikan ala pak Rahmat Banjar.
Kemarin baru menamatkan tafsir surah An-Najm Sayyid Quthb, Di Bawah Naungan Qur’an Jilid 11 (Gema Insani, 2004). Sayyid Quthb salah seorang pentolan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dihukum mati oleh presiden mesir Gamal Abdul Nasser atas tuduhan makar. Beliau pernah ditawari amnesti dengan syarat meminta maaf, Sayyid Quthb menolak. Mungkin karena tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan, atau Sayyid Quthb mencapai apa yang diimpi-impikannya, ketika derita dan bahagia sama saja. Seperti hadits dalam shahîh Ibnu Hibbân yang beliau kutip dalam tafsir surah An-Najm, penjelasan Rasulullah ketika ditanya tentang suhuf nabi Musa, poin ke 3 dari 5 poin yang bunyinya: “(3) Aku heran kepada orang yang telah meyakini akan adanya qadar (ketentuan) Allah, tetapi mengapa mereka marah-marah (bila sesuatu menimpa dirinya). ”
Sedikit tergagap memahami, Sayyid Quthb meskipun pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat namun tetap konservatif dalam syariat, pernah menyatakan tidak setuju dengan gaya beragama kaum Sufi yang menyepi dan menepi dari kehidupan dunia. Saat menafsirkan surah An-Najm mencari penjelasan mengapa kafir Qurays mau sujud bersama-sama Rasulullah seperti di ayat terakhir surah An-Najm, beliau seolah berada di waktu dan tempat kejadian (hal 84), beliau mengalami ‘perjalanan’ yang lazim dialami oleh kaum sufi saat ‘diperjalankan’ bila telah tiba waktunya menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Pada beberapa majelis khusus, redaksi pernah mendengarkan hadits dan tafsir ayat dibacakan lengkap dengan gambaran suasana ketika hadits dan atau ayat itu turun, bukan hanya sebab turun, namun juga rasa dan suasana ketika itu, sehingga konteksnya lebih utuh dalam satu bingkai pemahaman.
Kejadian yang dialami Sayyid Quthb dan beberapa ahli tafsir lainnya bukanlah sesuatu yang ajaib, bukan atas kemauan yang bersangkutan seseorang ‘diperjalankan’. Tidak ada yang ajaib bila Tuhan menghendaki. Penjelasan yang hampir ilmiah tentang ‘perjalanan pikiran’ menembus dimensi ruang dan waktu kira-kira seperti artikel “Berpikir Jernih” sebelum ini. Bukan hanya milik ahli tafsir dan kaum sufi, para ilmuwan, pemikir, perupa, seniman dan komposer musik juga terbiasa berpikir multi ruang (dan waktu) dalam satu keadaan dengan peruntukan yang berbeda-beda.
Syukurlah pikiran dan perspektif ternyata tidak kaku meski awalnya gagap, bisa menyesuaikan begitu memiliki data baru. Beliau ternyata tidak sekaku gambaran kami selama ini, termasuk gambaran tentang gerakan Ikhwanul Muslimin yang ikut dibesarkan mendiang. Kagum, beliau mencantumkan di halaman 87 riwayat tentang keheranan kafir Qurays, mengapa Rasulullah tidak pernah mencela Tuhan kaum Yahudi dan Nasrani tapi mencela Lata, Uzza dan Manna (berhala kafir Qurays).
Lepas dari tafsir surah An-Najm yang mengagumkan. Ada pendapat mendiang Sayyid Quthb yang sampai hari ini belum terbukti, kerusakan tatanan masyarakat adalah akibat dari tidak diterapkannya nilai dan syari’at Islam dalam suatu sistem kemasyarakatan. Kami pahami sebagai semangat mendiang ingin ‘mengislamkan’ tatanan dan sistem. Tanpa mengurangi rasa hormat pada mendiang, sampai hari ini sistem dan tatanan tidak bisa diislamkan atau dikafirkan. Sesuai tujuan agama-agama diturunkan untuk umat manusia, untuk bani Adam bukan untuk sistem.
Orang-orang di dalam sebuah sistem bisa diislamkan. Diislamkan bukan berarti harus beragama Islam, tapi Islam dalam arti nilai-nilai. Dan dalam nilai-nilai Islam ada nilai-nilai ajaran agama sebelumnya. Dalam ajaran Islam terkandung suhuf (lembar) Ibrahim, Musa dan Isa yang inti ajarannya tentang Tauhid (akidah) dan memanusiakan diri sendiri dan orang lain (kebaikan dan akhlak).
Masalahnya, mengislamkan diri sendiri dan umat islam sendiri belum selesai. Akidah adalah urusan pribadi tiap-tiap manusia dengan Tuhan yang sudah ditentukan sejak sebelum manusia dilahirkan ke dunia melalui keluarga dan lingkungan yang bagaimana, daerah ini diluar jangkauan manusia yang satu atas manusia yang lain, bukan hak manusia menghakimi manusia yang satu atas manusia lain. Seseorang bisa saja mengaku dan terlihat ahli Tauhid tapi ternyata masih menuhankan agama, kejayaan, golongan, kepopuleran, ras, ciptaan, uang, status sosial, materi dan lain-lain.
Pasangan akidah, yaitu akhlak masih dalam jangkauan. Bila akhlak beres, akidah dengan sendirinya akan ikut beres. Meski mirip, bebeda dimensi kesadaran dalam akhlak dengan etika-moral. Akhlak lahir dari kesadaran menghamba pada Pencipta, sedangkan etika dan moralitas lahir dari kesadaran bahwa dirinya sama dengan mahluk lain sesama ciptaan.
Kegagapan adalah proses. Bukan cuma dalam artikulasi membaca, juga ada dalam proses memahami, yang gagap belum tentu tidak lebih paham dari yang lancar.