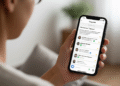Wartakita.id, SUMATERA — Di tengah puing-puing yang disisakan oleh Siklon Senyar, kita menyaksikan dua badai sekaligus. Pertama, badai alam yang menghancurkan rumah warga. Kedua, “badai konten” yang diciptakan oleh rombongan pejabat dan wakil rakyat yang turun ke lapangan.
Bukannya membawa dokumen rancangan undang-undang mitigasi bencana atau surat keputusan percepatan anggaran darurat (yang merupakan tupoksi utama mereka), memperbaiki regulasi pengelolaan hutan yang harus berpihak kepada rakyat dan alam, bukan kepada oligarki dan konco politik, mereka datang membawa tim dokumentasi lengkap dengan drone dan kamera mirrorless.
Pertanyaan pembaca kami sangat menohok: Mengapa mereka tidak bisa melihat peluang bekerja nyata lewat regulasi? Mengapa mereka tidak peduli bahwa rakyat sudah muak?
Jawabannya menyedihkan, namun logis secara politis. Berikut adalah bedah anatomi dari fenomena ini.
1. Ilusi “Kerja Nyata”: Regulasi Itu Abstrak, Foto Itu Konkrit
Secara psikologis, manusia (termasuk pemilih) memiliki bias kognitif yang disebut Availability Heuristic. Kita menilai kinerja seseorang berdasarkan apa yang paling mudah kita ingat dan kita lihat.
-
Regulasi (Tupoksi Sejati): Mengubah UU Penanggulangan Bencana agar birokrasi pencairan dana darurat lebih cepat adalah pekerjaan sunyi. Butuh waktu berbulan-bulan dan hasilnya berupa dokumen PDF yang tidak dibaca rakyat. Hasilnya (korban selamat karena sistem peringatan dini) bersifat intangible.
-
Konten (Pencitraan): Foto pejabat mengangkat satu sak semen atau memeluk korban yang menangis adalah visual instan. Itu mengirim sinyal primitif: “Saya Hadir. Saya Peduli.”
Bagi politisi, regulasi memiliki Return on Investment (ROI) politik yang rendah karena tidak visual. Sementara konten di lokasi bencana memiliki ROI politik instan.
2. Akar Kegagapan: Mengapa Pemda Terlambat (Lagi)?
Di balik hingar-bingar konten pejabat pusat, terdapat realitas sunyi yang mengerikan di level daerah: Paralisis Birokrasi. Kegagapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan merespons Siklon Senyar bukan semata karena ketidakmampuan, melainkan karena ketakutan struktural.
-
Jebakan Administratif (Hyper-Caution): Pejabat daerah tersandera ketakutan akan kriminalisasi anggaran. Dana Belanja Tak Terduga (BTT) seringkali mengendap karena Kepala Daerah takut “salah administrasi” yang berujung pemeriksaan aparat hukum di kemudian hari. Akibatnya, mereka menunggu “petunjuk teknis” dari pusat saat air sudah setinggi leher. Prosedur mengalahkan urgensi nyawa.
-
Mitigasi Kosmetik: Anggaran daerah selama ini habis untuk infrastruktur yang “terlihat” (gerbang kota, tugu, kantor dinas baru). Infrastruktur mitigasi “tak terlihat” seperti sistem drainase bawah tanah, sensor cuaca, atau pelatihan simulasi warga, dianaktirikan. Saat bencana datang, barulah ketahuan bahwa kita telanjang tanpa perlindungan.
-
Krisis Data: Kegagapan terjadi karena keputusan diambil berdasarkan feeling atau laporan ABS (Asal Bapak Senang), bukan data driven. Pemda seringkali tidak punya peta risiko mikro yang akurat, sehingga evakuasi dilakukan secara reaktif, bukan preventif.
3. “Disaster Fatigue”: Saat Pahlawan Asli Mulai Tumbang
Sementara pejabat datang silih berganti dengan baju lapangan yang masih licin dan wangi, ada sisi gelap di lapangan yang luput dari kamera: Overburn Tim SAR Gabungan dan Relawan.
Mereka telah bekerja non-stop 14 hari di lumpur. Kondisi mereka kini berada di titik nadir:
-
Kelelahan Fisik Ekstrem: Minim tidur, makan tidak teratur, dan paparan penyakit kulit/ISPA mulai menggerogoti fisik relawan dan Tim SAR.
-
Trauma Sekunder (Vicarious Trauma): Terus menerus mengevakuasi jenazah dan menghadapi tangisan keluarga korban menciptakan luka batin yang serius. Namun, tidak ada trauma healing bagi penolong; mereka dituntut terus kuat bak mesin.
-
Beban Ganda “Wisata Bencana”: Ini ironi terbesar. Bukannya fokus mencari korban, energi Tim SAR dan warga seringkali terkuras untuk melayani kunjungan VVIP. Menyiapkan tenda VIP, menjadi pemandu jalan bagi pejabat yang ingin foto, hingga rapat seremonial yang tidak perlu. Kehadiran rombongan pejabat seringkali justru menjadi beban logistik tambahan bagi warga yang sudah lelah fisik dan mental.
4. Paradoks “Bad Publicity is Still Publicity”
Mengapa pejabat tetap nekat ngonten meski dikritik? Jawabannya: Ya, absolut. Dalam algoritma media sosial, “kemarahan” adalah mata uang.
Tim media pejabat tahu betul hal ini. Biarkan bosnya viral karena dihujat dulu. Namanya naik di Top of Mind. Nanti, tim PR (Spin Doctors) akan masuk dengan narasi “klarifikasi”. Ini strategi sinis: membajak kebencian untuk mendulang popularitas.
5. Gelembung “Echo Chamber”
Mereka hidup dalam gelembung. Pejabat dikelilingi staf ahli yang hanya melaporkan vanity metrics: “Pak, video Bapak ditonton 2 juta kali!” tanpa melaporkan sentimen negatif di kolom komentar. Mereka bertaruh pada Silent Majority yang mungkin masih lugu, mengabaikan Vocal Minority yang kritis.
Solusi Konkrit: Stop Menonton, Mulai Menagih
A. Bagi Media: Berhenti memberitakan “kunjungan”. Audit kedatangannya: Apakah dia membawa logistik atau hanya merepotkan posko dengan minta jamuan? Angkat cerita kelelahan Tim SAR, bukan heroisme palsu politisi.
B. Bagi Masyarakat:
-
Starve the Beast: Stop share konten pejabat untuk menghujat. Itu memberi mereka panggung.
-
Lindungi Relawan: Jika ada pejabat datang dan merepotkan posko yang sedang sibuk, viralkan gangguan tersebut. Jadilah perisai bagi Tim SAR agar mereka bisa fokus bekerja.
C. Tuntutan Politik:
Tagih transparansi penggunaan Dana BTT. Tanyakan: “Berapa persen terserap? Kenapa lambat?” Paksa mereka bicara angka dan regulasi, bukan narasi simpati.
Sudahi Caper demi Eksposur
Tragedi Siklon Senyar membuka borok kita yang paling dalam. Di satu sisi, ada birokrasi yang gagap karena takut mengambil keputusan dan Tim SAR yang nyaris ambruk karena kelelahan. Di sisi lain, ada elit yang menjadikan penderitaan ini sebagai panggung catwalk politik.
Kita harus berhenti menormalisasi “Wisata Bencana”. Biarkan para penolong bekerja, biarkan birokrat memotong rantai administrasi, merombak dan merapikan carut marut tata kelola hutan agar berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup, dan biarkan politisi bekerja di ruang sidang merumuskan perlindungan masa depan—bukan di lokasi bencana demi konten TikTok.