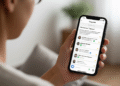KADAHANG, Sumba Timur — Pukul 03.30 subuh. Valentino Chris Doko sudah terbangun.
Bukan oleh alarm—ia tak punya listrik untuk mengisi baterai ponsel. Bukan oleh ayam berkokok—ayamnya mati seminggu lalu karena kelaparan di tengah kemarau panjang Sumba. Ia terbangun oleh sesuatu yang lebih tua dari segala teknologi: rasa lapar.
Di kegelapan total kamar yang hanya berdinding gedek bambu itu, Valen—begitu ia biasa dipanggil—meraba-raba mencari korek api. Lampu pelita minyak tanah dinyalakan. Cahaya kuning-jingga yang menyengat mata itu adalah satu-satunya melawan kegelapan yang membalut Desa Kadahang setiap malam.

Ririn, istrinya, sudah duduk terpekur di pojok kamar. Seruni, putri mereka yang berusia lima tahun, masih terlelap dengan wajah yang berkeringat meski malam masih dingin.
“Ikan lagi habis kemarin. Kalau hari ini nggak laku, kita makan apa besok?” bisik Ririn, suaranya parau.
Valen tidak menjawab. Ia tahu jawabannya, dan Ririn juga tahu. Mereka akan berhutang lagi pada toko kelontong Bu Mince di ujung kampung. Hutang mereka sudah Rp 200.000, dan Bu Mince sudah mulai menaikkan alis setiap kali Valen datang.
Di bawah cahaya pelita yang bergetar oleh angin yang menyusup di celah-celah dinding, Valen melihat tangannya sendiri—tangan yang pecah-pecah karena terlalu sering terendam air laut, tangan yang dulunya, sepuluh tahun lalu ketika ia masih menjadi tukang las di Kupang, bisa membuat pagar besi yang indah.
Tapi tanpa listrik, apa gunanya keahlian mengelas?
Malam itu, Valen tidak tahu bahwa dalam enam bulan, hidupnya akan berubah total. Bahwa ia akan berhenti mengejar ikan, dan mulai mengejar percikan api besi. Bahwa listrik yang akan datang bukan hanya membawa terang, tetapi membawa kembali harga diri.
Perjalanan yang Tidak Pernah Tiba
Pukul 04.15, Valen sudah mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan berbatu menuju Pelabuhan Waingapu.
Lima kilometer. Dalam kegelapan total. Tanpa lampu sepeda.
“Pernah tiga kali saya jatuh karena lubang yang tidak kelihatan,” kenangnya. “Siku saya ini—” ia menunjukkan bekas luka memanjang di siku kanannya— “ini saat jatuh karena rem saya blong. Untung kepala nggak kena batu.”
Di pelabuhan, ia harus tawar-menawar dengan nelayan untuk mendapat ikan yang masih segar dengan harga yang pas. Terlalu mahal, ia tak akan untung. Terlalu murah, berarti ikannya sudah tidak segar—dan tidak akan laku.
Lalu perjalanan kedua: mencari es batu. Toko es terdekat jaraknya tiga kilometer dari pelabuhan, arah yang berlawanan dengan desanya. Sepeda tuanya harus membawa beban 15 kilogram es plus 20 kilogram ikan.
“Kalau matahari sudah naik tinggi, es-nya mulai mencair. Ikan mulai bau. Kalau sudah bau, harga jatuh. Kadang malah nggak laku sama sekali,” katanya. “Hidup saya diatur oleh matahari. Kalau matahari menang, saya kalah.”
Ia harus berkeliling kampung sejak jam 7 pagi, menjajakan ikan dari rumah ke rumah. Berjalan kaki karena sepedanya sudah rusak parah sejak pagi tadi.
Pendapatan bersih setiap minggu: Rp 500.000.
Cukup untuk membeli beras 25 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula 2 kilogram, dan beberapa bumbu dapur. Tidak cukup untuk membeli sepatu sekolah baru untuk Seruni yang sudah sobek. Tidak cukup untuk berobat ketika Ririn demam berhari-hari bulan lalu.
Tidak cukup untuk bermimpi.
“Pejuang Kelistrikan” di Medan Perang Geografi
Yang tidak dilihat Valen adalah perjuangan ratusan kilometer dari desanya.
Luther Simon Rufus Tubulau, 28 tahun, teknisi PLN di Alor, NTT, sedang bertarung dengan gunung.
Kabupaten Alor adalah medan perang bagi siapa pun yang ingin membawa listrik. 60% wilayahnya tidak punya jalan beraspal. Medan berbukit-bukit dengan kemiringan hingga 45 derajat. Jurang-jurang yang tak terlihat dalamnya karena kabut.
“Saya ingat betul waktu itu, Oktober 2023, kami harus membawa trafo berbobot 500 kilogram naik ke desa yang ada di ketinggian 800 meter,” kenang Luther. “Tidak ada jalan mobil. Kami harus pakai kuda dan tenaga manusia. 15 orang, butuh 8 jam untuk sampai atas.”
Namun, yang paling berbahaya adalah perjalanan laut.
Untuk melistriki pulau-pulau kecil seperti Pulau Treweng, Luther dan timnya harus menyeberang dengan kapal motor kecil membawa material. Ombak di Laut Sawu tidak kenal ampun.
“Pernah satu kali, kapal kami hampir tenggelam,” katanya, matanya menerawang. “Ombak setinggi tiga meter menghantam dari samping. Kapal miring hampir terbalik. Material bergeser, orang-orang berteriak. Saya pikir itu hari terakhir saya.”
Luther selamat. Tapi ia tahu, pekerjaan ini bukan untuk orang yang takut mati.
“Kenapa saya lakukan? Karena saya tahu di ujung kabel yang kami pasang itu, ada keluarga seperti keluarga saya yang menunggu. Anak-anak yang ingin belajar. Ibu-ibu yang ingin dagang. Bapak-bapak yang punya keahlian tapi tidak bisa pakai karena tidak ada listrik.”
“Ini tanggung jawab kami sebagai pejuang kelistrikan.”
Malam yang Berbeda
18 Maret 2024. Valen ingat tanggal itu dengan sangat jelas.
Sore itu, ada keramaian di balai desa. Pak Yulius Ndapajawal, Kepala Desa, mengumpulkan warga. Di sampingnya berdiri beberapa orang berseragam PLN.
“Bapak-ibu sekalian,” suara Pak Yulius bergetar oleh emosi. “Setelah kita tunggu puluhan tahun… listrik akan masuk ke desa kita!”
Hening sejenak. Lalu riuh rendah. Beberapa ibu-ibu menangis.
Valen berdiri di belakang, tidak percaya. Ia sudah terlalu sering mendengar janji-janji yang tidak pernah datang.
Tapi kali ini berbeda. Petugas PLN menjelaskan: mereka akan membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 9,3 kilometer dari gardu induk terdekat. Jaringan Tegangan Rendah 8 kilometer untuk distribusi ke rumah-rumah. Dua unit gardu trafo berkapasitas 100 kVA.
200 kepala keluarga. 958 jiwa. Akan mendapat listrik.
“Berapa lama?” teriak seseorang dari belakang.
“Tiga bulan.”
Malam itu, Valen tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana ke masa lalu, sepuluh tahun silam di Kupang, ketika ia masih menjadi tukang las. Ia ingat suara desis las yang menembus besi. Ia ingat bau besi terbakar. Ia ingat kepuasan melihat hasil karyanya: pagar rumah yang kuat dan indah.
“Kalau listrik datang…” bisiknya pada Ririn yang sudah setengah tertidur. “Kalau listrik datang, aku bisa las lagi.”
Ririn tersenyum tipis. “Kamu bisa sayang. Pasti bisa.”
Tiga Bulan yang Panjang
Pembangunan dimulai.
Setiap hari, Valen melihat tiang-tiang listrik baru berdiri satu per satu. Petugas PLN bekerja dari pagi hingga sore. Menggali lubang untuk pondasi tiang di tanah yang keras seperti batu. Mengangkat tiang besi setinggi 12 meter dengan tangan karena alat berat tidak bisa masuk.
Tapi yang membuat Valen terkesan bukan pekerjaannya—melainkan dedikasi mereka.
“Saya lihat mereka tidur di rumah warga karena tidak sempat pulang. Makan seadanya. Bekerja di bawah terik matahari yang sangat panas. Beberapa kali saya lihat mereka sampai jatuh sakit,” kata Valen.
Ia juga ikut membantu, membawakan air minum, kadang membantu mengangkat material. Bukan karena diminta—tapi karena ia merasakan sesuatu yang lama tidak ia rasakan: harapan.
Namun, di tengah pembangunan, sebuah masalah muncul.
Trafo yang dijadwalkan tiba tertunda. Kapal yang membawa material dari Kupang mengalami kerusakan mesin. Pembangunan tertunda tiga minggu.
“Saat itu kami kecewa berat,” kenang Pak Yulius. “Orang-orang mulai pesimis lagi. Mulai bilang, ‘Ah, ini pasti seperti yang dulu-dulu, tidak jadi juga.'”
Tapi tim PLN tidak menyerah. Mereka mencari trafo alternatif. Mereka mengatur ulang jadwal. Mereka memastikan proyek tetap berjalan.
Malam Pertama Terang
20 Juni 2024. Pukul 18.00.
Seluruh warga Desa Kadahang berkumpul di lapangan desa. Anak-anak berlarian dengan riangnya. Ibu-ibu membawa makanan. Ini adalah perayaan yang sudah ditunggu.
Pak Yulius berdiri di depan, di sebelah panel listrik utama desa yang baru.
“Bapak-ibu, anak-anak sekalian…” suaranya bergetar. “Malam ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa kita… kita akan menyalakan listrik!”
Pak Yulius menekan saklar besar.
CTAK!
Seketika, 50 lampu jalan yang baru dipasang di sepanjang desa menyala serentak. Terang benderang.
Hening sejenak.
Lalu meledak tepuk tangan, teriakan, tangisan haru. Anak-anak melompat-lompat. Ibu-ibu saling berpelukan. Bapak-bapak saling berjabat tangan dengan mata berkaca-kaca.
Valen berdiri di tengah keramaian, melihat ke atas. Lampu-lampu jalan itu seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya.
Air mata.
“Terima kasih Tuhan… terima kasih PLN… terima kasih pemerintah…” bisiknya.

Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seruni belajar di bawah cahaya lampu listrik yang terang. Tidak ada lagi asap yang menyengat mata. Tidak ada lagi cahaya yang redup yang membuat matanya cepat lelah.
“Papa,” kata Seruni, matanya berbinar. “Sekarang aku bisa baca sampai habis satu buku!”
Percikan Api Baru
Keesokan harinya, Valen tidak pergi mencari ikan.
Ia menggunakan uang tabungan terakhirnya—Rp 3 juta yang dikumpulkan dari menjual ternak kambing—untuk membeli mesin las bekas dari Waingapu. Tidak bagus, tapi cukup untuk memulai.
Ia membangun bengkel sederhana di samping rumahnya. Beratap seng, berdinding bambu. Tapi baginya, itu adalah istana.
Hari pertama, tidak ada pesanan. Hari kedua, tidak ada juga.
Hari ketiga, Pak Yulius datang.
“Valen, aku butuh pagar untuk kandang sapi. Kamu bisa?”
Mata Valen berbinar. “Bisa, Pak! Pasti bisa!”
Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sepuluh tahun, Valen menyalakan mesin las.

BZZZZZTTTT!
Percikan api biru-putih menyembur dari ujung elektroda. Cahayanya begitu terang, memantul di dinding-dinding bambu bengkelnya. Bau besi terbakar menyeruak. Suara desis yang nyaring membelah keheningan malam Sumba.
Tangan Valen bergetar sedikit—bukan karena takut, tapi karena bahagia.
Ia kembali.
Enam Bulan Kemudian: Transformasi
Januari 2025. Bengkel Valen tidak pernah sepi.
Dari pagar rumah, teralis jendela, rangka pintu besi, hingga konstruksi atap baja ringan—Valen mengerjakan semuanya. Ia bekerja dari pukul 08.00 pagi hingga 22.00 malam. Sesuatu yang mustahil dilakukan tanpa listrik.
“Sekarang kalau ada pesanan mendesak, saya bisa kerja sampai tengah malam kalau perlu,” katanya sambil tersenyum. “Dulu? Maghrib saja sudah gelap total.”
Pendapatan bersihnya kini rata-rata Rp 3 juta per minggu—enam kali lipat dari saat ia jual ikan.
Tapi yang berubah bukan hanya angka di buku tabungan. Yang berubah adalah segala-galanya.
Seruni sekarang punya meja belajar sendiri dengan lampu baca. Ia tidak perlu lagi berdesak-desakan dengan orang tua di bawah satu lampu pelita. Nilainya di sekolah naik drastis.
Ririn membuka usaha sampingan: membuat kue untuk dijual. Dengan mixer listrik dan oven, ia bisa produksi 50 kue sehari. Pendapatan tambahan Rp 500.000 per minggu.
“Ini bukan sekadar uang,” kata Ririn, matanya berkaca-kaca. “Ini tentang tidak perlu malu lagi saat Seruni minta sesuatu. Tentang bisa ke dokter tanpa mikir berhari-hari. Tentang bisa tidur nyenyak karena tahu besok pagi kita punya penghasilan.”
“Tentang martabat.”
Efek Domino di Seluruh Desa
Cahaya di bengkel Valen menyalakan efek domino di seluruh Desa Kadahang.
Pak Markus, tukang kayu yang selama ini menyerut kayu secara manual dengan tenaga tangan, kini punya mesin serut listrik. Produktivitasnya naik tiga kali lipat.
Bu Yeni, yang punya warung kecil di pinggir jalan, kini bisa jualan es batu dan minuman dingin. Kulkas kecilnya adalah harta paling berharga. Omzetnya naik dari Rp 300.000 menjadi Rp 1,5 juta per minggu.
Pak Yohanis membuka usaha sewa sound system untuk acara-acara desa. Sesuatu yang mustahil tanpa listrik.
“Dulu, malam hari tidak ada kegiatan apa-apa,” kata Pak Yulius, Kepala Desa. “Sekarang? Desa ini hidup sampai malam. Ada yang jualan, ada yang kerja, anak-anak belajar, ada yang kumpul nonton TV bareng di rumah tetangga.”
“Listrik itu bukan cuma soal lampu terang. Ini soal menghidupkan potensi manusia yang selama ini mati karena kegelapan.”
Wajah Manusia dari Kedaulatan Energi
Di Jakarta, para pengambil kebijakan berbicara tentang megawatt, gigawatt, dan terawatt. Mereka berbicara tentang Green Super Grid senilai ratusan triliun rupiah. Mereka berbicara tentang target Net Zero Emission 2060.
Angka-angka besar. Visi besar.
Tapi di Desa Kadahang, kedaulatan energi punya wajah. Wajah Valentino Chris Doko, 25 tahun, mantan penjual ikan yang sekarang menjadi tukang las dengan omzet Rp 12 juta per bulan.
Kedaulatan energi punya aroma. Aroma besi terbakar yang keluar dari bengkel las Valen setiap malam, mengalahkan aroma tanah kering khas Sumba.
Kedaulatan energi punya suara. Suara desis las yang membelah kegelapan, suara mesin serut kayu Pak Markus, suara kulkas Bu Yeni yang berdengung mengawetkan es, suara tawa anak-anak yang belajar sampai malam tanpa terganggu asap pelita.
“Saya nggak ngerti soal Green Super Grid atau Smart Grid atau apa,” kata Valen sambil menyeka keringat di keningnya, setelah menyelesaikan pesanan pagar besi pesanan ke-7 minggu ini.
“Tapi saya tahu ini: listrik tidak memberikan saya keahlian mengelas. Keahlian itu sudah saya punya dari dulu. Yang diberikan listrik adalah kesempatan untuk menggunakan keahlian itu.”
“Listrik memberikan saya kembali harga diri saya.”
Ia diam sejenak, menatap percikan api yang keluar dari ujung mesin lasnya.
“Dan untuk itu, saya akan selamanya berterima kasih.”
Di bawah cahaya lampu neon 20 watt yang bersinar terang di bengkel kecil pinggir Desa Kadahang, di tengah deru mesin las yang membelah sunyinya malam Sumba Timur, konsep besar “Energi Berdaulat untuk Indonesia Kuat” menemukan wujudnya yang paling nyata.
Bukan dalam dokumen kebijakan setebal ratusan halaman.
Bukan dalam presentasi PowerPoint dengan grafik yang rumit.
Tapi dalam percikan api las yang menerangi wajah seorang ayah yang akhirnya bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk putrinya.
Satu keluarga. Satu desa. Satu kabel listrik.
Dikali dengan ribuan desa lain di seluruh nusantara yang masih menunggu giliran.
Inilah kedaulatan energi yang sesungguhnya: ketika energi memberdayakan, bukan hanya menerangi.
***
Catatan Penulis: Reportase ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi online dan offline. Beberapa detail percakapan telah direkonstruksi.