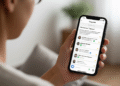Ada jenis kesepian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bekerja jauh dari rumah—di kota Palu yang masih asing di bulan keenam, mengurusi kabel-kabel infrastruktur IT yang dingin dan tak bicara.
Belasan tahun silam, dunia kerja saya adalah dunia yang terukur, presisi, dan logis. Tapi Ramadan selalu punya cara untuk menyelundupkan sesuatu yang tidak logis ke dalam dada.
Malam itu, usai azan Magrib, saya duduk sendirian di warung sari laut. Di depan saya: ikan kakap goreng kering dan sambal dabu-dabu yang segar. Secara fisik, saya adalah definisi dari kesendirian.
Lalu sepasang tamu duduk tak jauh dari meja saya.
Seorang bapak dengan pakaian yang masih meninggalkan jejak debu semen. Dan putri kecilnya—berseragam merah-putih, mungkin baru kelas satu SD.
Mereka memesan dua piring nasi putih. Hanya satu piring ayam goreng.
Saya tertegun.
Sang bapak dengan telaten menyuwir ayam goreng itu, memastikan bagian yang paling empuk mendarat di piring putrinya. Mereka makan dalam ritme yang sangat lambat—seolah ingin momen itu berlangsung selama mungkin. Tak ada gawai di tangan, tak ada distraksi. Hanya percakapan kecil, tawa malu-malu sang bocah, dan tatapan mata sang bapak yang penuh binar. Binar yang tidak bisa dibeli dengan gaji tenaga ahli mana pun.
Di meja saya, ikan kakap goreng tiba-tiba terasa hambar. Bukan karena rasanya salah—tapi karena saya baru menyadari betapa mewahnya apa yang mereka miliki.
Ada dorongan kuat untuk memesankan mereka menu tambahan. Satu piring ayam lagi. Mungkin udang goreng mentega.
Tapi saya ingat apa yang kita bicarakan kemarin tentang ego. Keinginan untuk memberi, kalau tidak hati-hati, bisa melukai martabat orang yang kita beri. Saya takut tawaran saya akan merusak momen “pahlawan” sang bapak di mata putrinya. Saat itu, di warung kecil itu, ia sedang merasa menjadi pria paling kaya di dunia. Saya tidak ingin menghancurkan itu.
Maka saya memilih jalan yang paling sunyi.
Saya selesaikan makan saya. Saya menuju kasir. Saya bayar tagihan meja saya—dan tagihan meja mereka. Lalu saya pergi sebelum mereka menyadarinya.
Di jalan kembali ke penginapan, di bawah langit kota kecil yang tenang, ada kehangatan yang mengalir deras di dada saya. Lebih mengenyangkan dari ikan kakap yang baru saja saya makan.
Inilah yang mulai tersingkap di hari keempat ini: bahwa kebahagiaan sejati sering kali bukan berasal dari apa yang masuk ke perut kita, melainkan dari apa yang terpancar dari hati orang lain—dan berhasil kita rasakan.
Kemarin kita belajar tentang lapar sebagai bahasa empati. Malam itu saya belajar bahwa lapar juga bisa menjadi jembatan. Meskipun tidak ada satu kata pun yang saya ucapkan kepada bapak itu, ada sesuatu yang sempat bersentuhan di antara kami—di ruang makan yang sederhana itu, di antara dua piring nasi dan satu ayam goreng.
Kadang Tuhan memperlihatkan wajah-Nya lewat hal-hal seperti ini: suwiran ayam goreng dari tangan seorang bapak untuk putrinya. Tidak perlu menunggu kematian untuk menjumpai keindahan ilahiah. Ia hadir di warung-warung kecil, di momen-momen yang tidak sempat kita foto.
Kita tidak pernah benar-benar sendirian—jika kita mampu merasakan kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan kita sendiri.
Bukan sebaliknya, derita orang lain jadi sumber kebahagiaan kita, atau kebahagiaan orang lain menjadi sumber penderitaan kita.
Itulah infrastruktur yang paling penting untuk kita bangun: kabel-kabel kasih sayang yang menghubungkan satu hati dengan hati lainnya, melampaui sekat kelas, jabatan, dan pakaian berdebu.
Selamat menikmati perjamuan batin, di meja mana pun Anda berada malam ini.