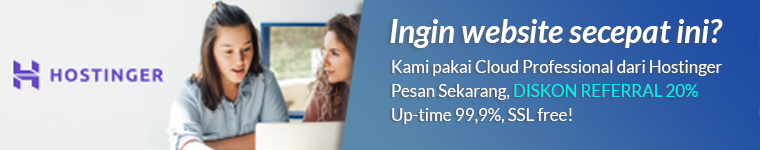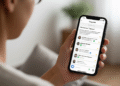WARTAKITA.ID, JAKARTA — Di sebuah lahan seluas 200 hektare di Kalimantan Selatan, pemandangan yang tak biasa terlihat. Seorang pemuda berusia 27 tahun, mengenakan jaket lapangan dan topi petani, berdiri dengan tablet di tangannya. Jari-jarinya dengan cekatan menggerakkan layar sentuh, menganalisis data kelembaban tanah, kadar nitrogen, dan proyeksi cuaca untuk tujuh hari ke depan. Di atas kepalanya, sebuah drone terbang melayang, merekam kondisi tanaman dari ketinggian 50 meter, mengirimkan data visual secara real-time ke sistem yang ia operasikan.
Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah. Ini adalah realitas baru pertanian Indonesia di tahun 2025. Dan pemuda itu—bersama 6,18 juta petani milenial lainnya di seluruh Indonesia—adalah wajah masa depan ketahanan pangan nasional.
6,18 Juta: Angka yang Menentukan Nasib Bangsa
Menurut data Sensus Pertanian (ST) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik, dari total 28,19 juta petani di Indonesia, sebanyak 6,18 juta orang atau 21,93% adalah petani milenial berusia 19–39 tahun. Angka ini mungkin terdengar kecil—hanya seperlima dari total petani. Namun, signifikansinya jauh melampaui proporsi numeriknya.
Petani milenial adalah garis pertahanan terakhir melawan krisis regenerasi petani yang telah mengancam Indonesia selama bertahun-tahun. Data BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir (2013-2023), proporsi petani berusia 55 tahun ke atas terus meningkat—dari 32,76% menjadi 39,45%. Ini artinya hampir 40% petani Indonesia kini sudah lanjut usia, dan dalam 10-15 tahun ke depan, mereka akan pensiun. Jika tidak ada generasi muda yang menggantikan, Indonesia akan menghadapi krisis pangan yang sangat serius.
Di sinilah 6,18 juta petani milenial menjadi sangat krusial. Mereka bukan hanya pengganti generasi tua, tetapi juga agen transformasi yang membawa pendekatan baru dalam pertanian: melek teknologi, berorientasi bisnis, dan peduli keberlanjutan.
Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, pernah mengungkapkan kekhawatirannya: “Hanya sekitar 8 persen dari total petani kita yang berusia 20-39 tahun. Sisanya lebih dari 90 persen masuk kategori petani kolonial, atau petani yang sudah tua.” Namun, ia menambahkan dengan optimis: “Tapi yang 8 persen ini adalah game-changer. Mereka adalah petani yang paham teknologi, yang mau belajar, yang punya visi untuk berkembang.”
Savira, Sandi, dan Husni: Wajah-Wajah Revolusi Pertanian

Savira Alvina Syakur: Dari Kebun Kopi ke Kafe Kopi Gunung—Rp90 Juta per Bulan
Savira Alvina Syakur, petani milenial asal Bandung, Jawa Barat, tidak hanya menanam kopi. Ia mengelola seluruh rantai nilai kopi—dari hulu ke hilir. Dimulai dari kebun kopi di lereng pegunungan, ia mengontrol setiap tahap: penanaman, pemanenan, pengolahan biji, roasting, hingga penjualan.
Tapi Savira tidak berhenti di situ. Ia mendirikan Kafe Kopi Gunung, sebuah kafe yang menjual produk kopi dari kebunnya sendiri. Dengan strategi hilirisasi ini, ia tidak hanya mendapat untung dari penjualan biji kopi mentah (yang marginnya tipis), tetapi juga dari penjualan produk olahan bernilai tambah tinggi. Hasilnya? Omzet hingga Rp90 juta per bulan.
“Kalau petani tradisional hanya jual biji kopi mentah, mereka dapat harga Rp50.000-70.000 per kilogram. Tapi kalau kita olah sendiri jadi produk jadi, kita bisa jual Rp200.000-300.000 per kilogram. Bedanya sangat besar,” jelas Savira.
Strategi Savira adalah contoh sempurna dari petani milenial sebagai entrepreneur. Mereka tidak lagi hanya menjadi produsen bahan mentah yang selalu berada di posisi tawar yang lemah. Mereka menjadi pelaku bisnis yang mengendalikan rantai nilai, menciptakan brand sendiri, dan meraih margin keuntungan yang jauh lebih besar.
Sandi Octa Susila: Duta Petani Milenial dengan Drone dan IoT
Sandi Octa Susila adalah sosok yang mewakili sisi teknologi dari revolusi pertanian. Sebagai salah satu Duta Petani Milenial yang dikukuhkan oleh Kementerian Pertanian, Sandi telah mengintegrasikan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) dan drone dalam pengelolaan lahan hortikulturanya.
Menggunakan sensor IoT, Sandi memantau kelembaban tanah, suhu, dan kadar nutrisi secara real-time melalui aplikasi di smartphone-nya. Jika ada anomali—misalnya tanah terlalu kering—sistem otomatis mengirimkan notifikasi, dan ia bisa mengaktifkan irigasi dari jarak jauh. Drone yang ia operasikan tidak hanya untuk dokumentasi, tetapi juga untuk pemetaan lahan, deteksi dini hama, dan bahkan penyemprotan pestisida yang lebih presisi dan efisien.
“Dengan teknologi ini, saya bisa mengelola lahan yang jauh lebih luas dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Efisiensi meningkat drastis,” ujar Sandi.
Tapi kontribusi Sandi tidak berhenti pada lahannya sendiri. Ia juga membangun jaringan dengan lebih dari 300 petani di wilayahnya, berbagi pengetahuan tentang teknologi, dan bahkan membantu meningkatkan efisiensi rantai distribusi pertanian. Dengan membentuk kelompok tani yang terorganisir, mereka bisa bernegosiasi dengan pembeli dalam posisi yang lebih kuat, mendapatkan harga yang lebih baik, dan margin keuntungan yang lebih besar.
Husni: Mengelola 480 Hektare dengan Sistem Semiintensif—Omzet Rp90 Juta per Bulan
Husni adalah contoh petani milenial yang sukses dalam skala besar. Di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Ushuluddin yang ia kelola, Husni mengelola:
- 20 hektare padi sawah
- 80 hektare perkebunan karet
- 30 hektare kelapa sawit
- 250 ekor sapi potong yang dipelihara dengan sistem open grazing di lahan seluas 480 hektare
Yang menarik dari pendekatan Husni adalah penggunaan sistem semiintensif dalam peternakan sapi. Sapi-sapi tidak dikandangkan sepanjang hari, tetapi dilepas untuk merumput di padang penggembalaan pada pagi hari, dan dimasukkan ke kandang pada sore hari. Untuk mengendalikan pergerakan sapi, Husni menggunakan paddock dari kabel listrik—sebuah teknologi sederhana namun efektif yang memungkinkan sapi tetap dalam pengawasan meskipun berkeliaran bebas.
Diversifikasi usaha dan penerapan teknologi modern ini menghasilkan omzet hingga Rp90 juta per bulan—angka yang sangat mengesankan untuk usaha pertanian dan peternakan. Husni membuktikan bahwa dengan skala yang tepat, manajemen yang baik, dan teknologi yang sesuai, pertanian bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan.
Rp30 Triliun: Komitmen Pemerintah untuk Brigade Milenial
Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, tidak tinggal diam melihat potensi besar dari petani milenial ini. Pada November 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan peluncuran Program Petani Milenial dengan dukungan dana sebesar Rp30 triliun—salah satu program pertanian terbesar dalam sejarah Indonesia.
Program ini menargetkan untuk mencetak 100.000 petani milenial di 10 provinsi prioritas. Setiap tim yang terdiri dari 15 petani muda akan menerima modal sebesar Rp3 miliar untuk mengelola lahan seluas 200 hektare. Hingga saat ini, sudah ada 23.000 orang yang mendaftar, dan 3.000 di antaranya sudah aktif di lapangan.
Menteri Amran menjelaskan konsep program ini dengan gamblang: “Bagi sarjana, mereka bisa menjadi manajer. Yang berlatar belakang teknik bisa menjadi mekanik. Dan lulusan SMA akan menjadi operator. Generasi milenial yang paham teknologi akan mengoperasikan alat seperti drone dan aplikasi berbasis IT.”
Ini adalah konsep pertanian sebagai industri modern yang membutuhkan SDM dengan berbagai keahlian—bukan lagi sekadar tukang tanam yang mengandalkan kekuatan fisik. Petani milenial adalah manajer agribisnis, teknisi mesin pertanian, analis data, dan digital marketer—semuanya dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan, telah menyatakan apresiasi terhadap program ini. “Saya minta kepada para penyuluh untuk terus belajar mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis dan manajemen. Petani harus menjadi profesi yang paling menjanjikan,” ujarnya.
Kalimantan Selatan: 1.000+ Petani Milenial Turun Langsung di Cetak Sawah

Salah satu kisah sukses implementasi Program Petani Milenial adalah di Kalimantan Selatan. Menteri Amran, dalam kunjungan kerjanya ke Desa Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala (22/11/2024), menyaksikan langsung antusiasme generasi muda untuk terjun ke pertanian.
“Alhamdulillah dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, ada lebih dari 1.000 milenial yang turun langsung pada program cetak sawah. Kami bagikan mesin-mesin modern untuk mereka gunakan,” kata Amran dengan bangga.
Program cetak sawah di Kalimantan Selatan adalah proyek ambisius untuk mengubah lahan marginal dan rawa menjadi sawah produktif. Dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan jaringan irigasi, dan Kementerian Pertanian dalam penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) modern, program ini menjadi ajang pembuktian bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi ujung tombak swasembada pangan.
Dody, perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, menegaskan dukungan penuh terhadap program ini: “Kementerian PU mendukung sektor pertanian dan Program Petani Milenial melalui pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi pompa air, pintu air, tanggul, serta bendungan untuk memastikan pasokan air yang memadai dan efisien. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memastikan regenerasi petani di Indonesia.”
Teknologi: Dari IoT hingga Artificial Intelligence
Salah satu ciri khas yang membedakan petani milenial dari generasi sebelumnya adalah adopsi teknologi. Menurut data ST 2023, dari total petani milenial berusia 19-39 tahun, sebagian besar di antaranya adalah pengguna aktif teknologi digital—mulai dari smartphone untuk akses informasi cuaca dan harga pasar, hingga aplikasi pertanian canggih yang berbasis kecerdasan buatan (AI).
Aplikasi Plantix: Diagnosis Penyakit Tanaman dengan AI

Salah satu aplikasi yang populer di kalangan petani milenial adalah Plantix. Aplikasi ini menggunakan teknologi pengenalan gambar berbasis AI untuk mendiagnosis penyakit tanaman. Petani cukup mengambil foto daun atau bagian tanaman yang sakit, dan aplikasi akan memberikan diagnosis otomatis serta rekomendasi perawatan.
Hingga kini, Plantix mampu mendeteksi lebih dari 30 jenis tanaman utama dan 400 penyakit, dengan tingkat akurasi diagnosis hingga 90 persen. Aplikasi ini juga menyediakan fitur kalkulator pupuk yang membantu petani menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman.
“Dulu kalau tanaman sakit, kita hanya bisa tebak-tebak atau tanya ke petani tua. Sekarang tinggal foto, langsung tahu penyakitnya apa dan obatnya apa,” ujar Jajang Tauhidin, peserta Program Petani Milenial dari Purwakarta yang berhasil meningkatkan omzetnya hingga 2,5 kali lipat setelah menggunakan teknologi digital.
Drone: Pemetaan Lahan dan Penyemprotan Presisi
Teknologi drone juga semakin banyak digunakan oleh petani milenial. Drone tidak hanya untuk dokumentasi atau foto udara yang keren untuk media sosial, tetapi memiliki fungsi praktis yang sangat bermanfaat:
- Pemetaan Lahan: Drone dilengkapi dengan kamera multispektral dapat menghasilkan peta detail kondisi lahan, menunjukkan area mana yang subur dan area mana yang kekurangan nutrisi.
- Deteksi Dini Hama: Dengan analisis citra dari drone, petani bisa mendeteksi serangan hama atau penyakit pada tahap awal, bahkan sebelum terlihat oleh mata telanjang.
- Penyemprotan Pestisida: Drone penyemprot dapat menjangkau lahan yang luas dengan lebih cepat dan efisien, menghemat tenaga kerja dan mengurangi paparan pestisida terhadap manusia.
Rayndra, seorang petani milenial yang menjadi penerima bantuan program Pertumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dari Kementerian Pertanian pada 2016 dengan dana Rp30 juta, menggunakan drone untuk mengelola lahan pertanian dan peternakan kombinasinya. “Dengan drone, saya bisa memantau kondisi seluruh lahan dalam waktu 30 menit. Dulu butuh satu hari penuh untuk keliling periksa satu per satu,” ungkapnya.
IoT Sensor dan Sistem Otomatis

Internet of Things (IoT) telah mengubah total cara petani mengelola lahan. Sensor kelembaban tanah yang ditanam di berbagai titik lahan akan mengirimkan data secara real-time ke server pusat. Jika kelembaban turun di bawah ambang batas, sistem irigasi otomatis akan menyala tanpa perlu intervensi manual.
Sensor suhu dan kelembaban udara membantu petani memprediksi risiko serangan jamur atau hama tertentu. Sensor NPK tanah memberikan informasi tentang kadar nitrogen, fosfor, dan kalium, sehingga pemupukan bisa dilakukan secara presisi—tidak berlebihan (yang boros biaya dan merusak lingkungan) dan tidak kekurangan (yang menurunkan produktivitas).
Taufik Mawaddani, petani muda asal Jogja yang mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian, mengintegrasikan sistem IoT dengan dashboard digital yang bisa diakses melalui smartphone. “Saya bisa pantau kondisi lahan dari mana saja. Kalau ada masalah, saya langsung tahu dan bisa ambil tindakan cepat,” katanya.
Jawa Timur Juaranya: 971.102 Petani Milenial
Data ST 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah petani milenial terbanyak, mencapai 971.102 orang, diikuti Jawa Tengah dengan 625.807 orang dan Jawa Barat dengan 543.044 orang. Di sisi lain, DKI Jakarta mencatat angka terendah dengan hanya 2.568 orang—yang memang logis mengingat Jakarta adalah wilayah urban dengan lahan pertanian yang sangat terbatas.
Penyebaran ini menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tradisi agraris kuat cenderung memiliki konsentrasi petani muda lebih tinggi. Namun, yang menarik adalah bahwa di daerah-daerah ini, petani milenial tidak hanya melanjutkan tradisi lama, tetapi mengubahnya dengan pendekatan baru.
Di Jember, Jawa Timur, misalnya, ada Sucipto yang sebelumnya bertani secara tradisional dengan hasil pas-pasan. Setelah bergabung dengan Program Makmur dan mendapat pendampingan, ia kini menggunakan aplikasi untuk mencatat hasil panen dan menghitung keuntungan. “Dulu saya tidak tahu pasti untung atau rugi. Sekarang semua tercatat di HP. Saya tahu persis berapa modal, berapa hasil, dan berapa untung bersih,” ujarnya.
Perempuan Milenial: Minoritas yang Berpotensi Besar
Dari 6,18 juta petani milenial, berdasarkan jenis kelaminnya, masih didominasi oleh laki-laki yaitu 89,03% (sekitar 5,5 juta orang) sedangkan perempuan hanya 10,97% (sekitar 1,84 juta orang). Kesenjangan gender ini mencerminkan masih kuatnya stigma bahwa pertanian adalah pekerjaan laki-laki.
Namun, perempuan petani milenial seperti Lodiana Lae dari NTT, atau Jatu Barmawati yang mendirikan Agriculture Youth Organization (AYO), membuktikan bahwa perempuan tidak hanya mampu bertani, tetapi juga menjadi pemimpin dan inovator dalam sektor ini.
Jatu percaya bahwa komoditas hasil pertanian di Indonesia memiliki kualitas baik dan tidak kalah dengan negara lain. Melalui AYO, ia dan komunitasnya berupaya membina generasi muda—termasuk perempuan dan penyandang disabilitas—agar mencintai dunia pertanian. “AYO mengusung tiga nilai utama: education, agro-sociopreneur, dan kolaborasi. Kami ingin membuktikan bahwa pertanian adalah untuk semua orang, tanpa memandang gender atau kemampuan fisik,” ujarnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan kesetaraan gender dalam akses terhadap pelatihan, modal, dan teknologi pertanian. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pertanian.
Tantangan: Stigma, Infrastruktur, dan Perubahan Iklim
Meskipun optimisme tinggi, petani milenial menghadapi berbagai tantangan serius:
1. Stigma Sosial
Banyak orang tua yang tidak mendukung anak mereka terjun ke pertanian karena menganggapnya tidak memiliki masa depan cerah. Bahkan di kalangan teman sebaya, mengaku sebagai petani sering dianggap “kurang keren” dibandingkan profesi lain seperti pegawai kantoran atau startup worker.
Rayndra, yang memilih berkuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta jurusan Peternakan, mengakui sempat mendapat pertentangan dari keluarga. “Keluarga saya menganggap dunia pertanian atau peternakan kurang menguntungkan. Tapi saya tetap bersikeras dan berjuang untuk membuktikan bahwa dengan menekuni pertanian dan peternakan pun, saya bisa sukses,” katanya.
2. Infrastruktur yang Belum Merata
Akses jalan yang buruk di daerah pedesaan membuat biaya transportasi hasil panen menjadi sangat mahal. Jaringan internet yang lemah menghambat adopsi teknologi digital. Akses ke listrik yang tidak stabil membuat sulit untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan refrigerasi atau mesin-mesin modern.
3. Perubahan Iklim
Cuaca yang semakin tidak menentu menjadi ancaman nyata. Curah hujan yang ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan serangan hama baru yang lebih ganas adalah tantangan yang harus dihadapi setiap musim tanam.
4. Akses Modal
Meskipun pemerintah telah menyediakan program pembiayaan, tidak semua petani muda memiliki akses mudah ke permodalan. Proses administrasi yang rumit, persyaratan agunan, dan bunga yang masih dianggap tinggi menjadi hambatan.
Masa Depan: Menuju 100.000 Petani Milenial pada 2026
Target pemerintah untuk mencetak 100.000 petani milenial melalui program resmi adalah ambisi yang realistis namun menantang. Dengan 23.000 orang yang sudah mendaftar dan 3.000 yang aktif di lapangan, momentum sudah terbangun. Yang dibutuhkan adalah:
- Sosialisasi Masif: Agar lebih banyak anak muda tahu bahwa pertanian bisa menjadi profesi yang menjanjikan.
- Simplifikasi Akses Modal: Membuat proses pendaftaran dan pencairan dana lebih mudah dan cepat.
- Infrastruktur Pendukung: Perbaikan jalan, internet, listrik, dan irigasi di daerah-daerah pertanian.
- Pasar yang Pasti: Memastikan ada pembeli tetap untuk hasil panen, sehingga petani tidak khawatir soal pemasaran.
- Kampanye Perubahan Mindset: Mengubah stigma negatif tentang pertanian menjadi narasi positif bahwa petani adalah profesi modern, menguntungkan, dan mulia.
Kesimpulan: Brigade Pangan Menentukan Nasib Bangsa
Menteri Amran menyebut petani milenial sebagai “Brigade Swasembada Pangan”—sebuah julukan yang tepat. Mereka adalah sosok anak muda, penampilan keren dengan peralatan dan teknologi pertanian mutakhir, dan mandiri secara finansial. Mereka adalah harapan terakhir Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan global.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat—seperti penurunan harga pupuk 20% yang baru saja diumumkan, revitalisasi industri pupuk, digitalisasi distribusi melalui i-Pubers, dan Program Petani Milenial senilai Rp30 triliun—6,18 juta petani milenial ini memiliki peluang besar untuk sukses. Dan ketika mereka sukses, Indonesia sukses. Ketika mereka makmur, rakyat Indonesia makan dari hasil tanah sendiri, bukan impor dari negara lain.
Bustanul Arifin, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), pernah mengajukan pertanyaan retoris: “Apakah berkurangnya tenaga muda di sektor pertanian membuat mereka tidak punya pilihan lain untuk terus bekerja sebagai petani? Atau sebenarnya kita tidak lagi membutuhkan petani muda?”
Jawabannya jelas: Kita sangat membutuhkan petani muda. Mereka adalah masa depan. Dan masa depan itu sudah dimulai—di lahan-lahan seluas 200 hektare, dengan drone yang terbang di atas kepala, dengan sensor IoT yang tertanam di tanah, dengan aplikasi di smartphone yang memberikan insight real-time, dan dengan 6,18 juta anak muda yang membuktikan bahwa pertanian adalah profesi abad 21.
***
Catatan Penulis: Artikel ini ditulis berdasarkan data resmi dari Sensus Pertanian 2023 BPS, Kementerian Pertanian, dan catatn wawancara dengan berbagai petani milenial di seluruh Indonesia yangb tersedia secara daring. Data jumlah petani milenial (6,18 juta orang, 21,93% dari total petani) dan Program Petani Milenial (Rp30 triliun, target 100.000 petani) bersumber dari dokumen resmi pemerintah. Kisah-kisah individu seperti Savira, Sandi, Husni, dan lainnya dikutip dari berbagai sumber media dan publikasi terpercaya.