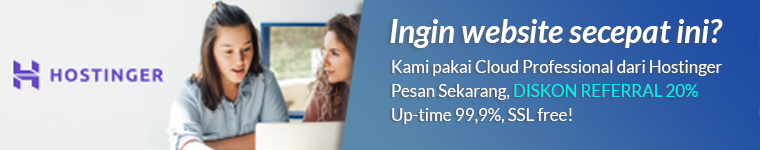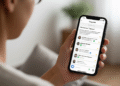Setiap 1 Mei, Hari Buruh mengingatkan kita pada perjuangan panjang pekerja untuk mendapatkan hak dan kesejahteraan. Namun, di tengah lautan spanduk dan orasi, ada pertanyaan yang menggelitik: bagaimana nasib buruh Indonesia di era digital yang bergerak cepat? Digitalisasi, dengan segala kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan ekonomi gig, telah mengubah wajah dunia kerja.
Bagi sebagian, ini adalah peluang emas; bagi yang lain, ancaman nyata. Sebagai saksi perubahan ini, saya merenungkan pengalaman melihat seorang driver ojek online yang bekerja hingga larut malam demi memenuhi target harian, sebuah pemandangan yang kini menjadi cermin perjuangan buruh modern di Indonesia.
Digitalisasi membuka peluang besar bagi buruh Indonesia, terutama generasi muda. Platform seperti Gojek, Grab, dan Shopee telah menciptakan lapangan kerja baru, memberikan fleksibilitas yang sebelumnya sulit diakses pekerja informal. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sektor ekonomi digital menyumbang lebih dari 10% PDB Indonesia, dengan jutaan pekerja bergabung sebagai mitra pengemudi, penjual online, atau freelancer.
Bagi seorang ibu rumah tangga di pinggiran Jakarta yang kini berjualan di marketplace atau seorang mahasiswa yang menjadi content creator, teknologi menawarkan kebebasan finansial dan kesempatan untuk bermimpi lebih besar. Saya pernah berbincang dengan seorang teman yang beralih dari pekerja kantoran menjadi freelancer desain grafis, dan ia mengaku lebih bahagia dengan fleksibilitas yang diberikan platform seperti Upwork.
Namun, di balik peluang itu, ancaman digitalisasi tak kalah nyata. Ekonomi gig sering kali menjebak buruh dalam lingkaran ketidakpastian. Upah yang bergantung pada algoritma, minimnya jaminan sosial, dan persaingan ketat membuat pekerja seperti driver ojek online atau kurir logistik bekerja hingga batas fisik mereka.
Sebuah laporan dari International Labour Organization (ILO) pada 2023 menyebutkan bahwa 70% pekerja gig di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan atau dana pensiun.
Saya teringat seorang driver yang mengeluh tentang potongan komisi besar dari platform, membuatnya sulit menabung meski bekerja lebih dari 12 jam sehari. Ditambah lagi, otomatisasi mengancam pekerjaan tradisional; mesin dan robot kini mulai menggantikan buruh pabrik dan pekerja ritel, meninggalkan mereka yang tak punya keterampilan digital dalam ketidakpastian.
Refleksi atas fenomena ini membawa saya pada pertanyaan: apakah digitalisasi benar-benar membebaskan buruh, atau justru menciptakan bentuk eksploitasi baru? Hari Buruh 2025 seharusnya menjadi momentum untuk tidak hanya merayakan, tetapi juga mengkaji ulang bagaimana teknologi dapat diarahkan untuk kesejahteraan pekerja.
Pemerintah dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama menciptakan regulasi yang melindungi hak buruh digital, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan pelatihan keterampilan. Solidaritas antarburuh juga harus diperkuat, misalnya melalui serikat pekerja digital yang memperjuangkan kepentingan bersama.
Saat melihat driver ojek online itu kembali melaju di tengah malam, saya merasa teknologi telah memberikan harapan sekaligus beban. Digitalisasi adalah pisau bermata dua: ia bisa menjadi tangga menuju kesejahteraan atau jurang ketimpangan baru.
Hari Buruh bukan sekadar seruan untuk upah layak, tetapi juga panggilan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak meninggalkan buruh Indonesia di belakang. Kita semua, sebagai bagian dari masyarakat digital, punya tanggung jawab untuk menjawab tantangan ini—demi masa depan kerja yang lebih manusiawi.