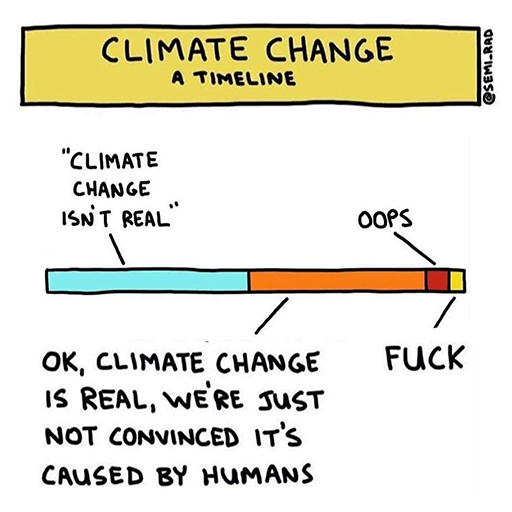“Sebelum manusia mengenal pers dalam berbagai format dan media, baik buruk peradaban suatu bangsa ditentukan oleh senimannya. Bila buruk, salahkan senimannya, bila baik itu karena jasa para pendidik.”
Kata mendiang Ali Walangadi beberapa tahun silam dalam sebuah obrolan lepas. Pers diposisikan mendiang yang seniman sebagai pengganti perannya dalam membangun peradaban.
Pers masa kini dengan jejaring sumber informasi, cakupan wilayah penyebaran berita, bank data dan lain-lain, memang bisa mengarahkan arah perkembangan peradaban suatu bangsa.
Kekuatan pers dalam membentuk opini dan membangun kesadaran sebuah masyarakat disadari betul oleh para diktator dan pemilik modal. Sesekali pers, kekuasaan dan kapitalisme saling memanfaatkan bila kebetulan sedang menuju arah yang sama.
Simbiosis mutualisme ketiganya pada rentang masa tertentu, mungkin sekali pernah (atau sering?) menempatkan masyarakat sebagai ‘korban’.
Tibalah era internet, disusul sosial media yang memungkinkan warga masyarakat non jurnalis menjadi pewarta. Gunung Etna meletus di Italia, sekian menit gambar dan cuitan warga yang berada di lokasi muncul di media sosial. Dulu dengan komputer desktop, kini lewat ponsel di tangan. Makin cepat, bisa dimana saja dan makin praktis. Signal, baterai portabel dan colokan PLN adalah koentji.
 Informasi berupa foto jembatan gantung yang putus di Bone yang disebarkan netizen bulan Maret tahun 2015 lalu, kini telah diperbaiki. Anak-anak SD tidak perlu lagi menembus deras arus sungai saat menuju sekolah (link berita).
Informasi berupa foto jembatan gantung yang putus di Bone yang disebarkan netizen bulan Maret tahun 2015 lalu, kini telah diperbaiki. Anak-anak SD tidak perlu lagi menembus deras arus sungai saat menuju sekolah (link berita).
Foto jasad bocah Alan Kurdi pengungsi Suriah terbujur kaku di pantai Turki menggugah kemanusiaan masyarakat dunia.
 Internet mengokohkan dua kosa kata baru: netizen dan citizen journalism. Bila dulu hanya pers formal yang bisa ‘memanipulasi’ opini, kini setiap orang bisa saling memanipulasi. Bagian dari manipulasi untuk kebaikan atau keburukan, pilihannya ada pada ujung jari.
Internet mengokohkan dua kosa kata baru: netizen dan citizen journalism. Bila dulu hanya pers formal yang bisa ‘memanipulasi’ opini, kini setiap orang bisa saling memanipulasi. Bagian dari manipulasi untuk kebaikan atau keburukan, pilihannya ada pada ujung jari.
Kecepatan aliran data, informasi, opini dan berita tidak terbendung. Sayangnya, perangkat cerdas tidak seketika mencerdaskan pemiliknya. Belum diikuti dengan peningkatan kesabaran mencerna dan kejernihan pikir. Alih-alih melatih kesabaran, beberapa media malah memanfaatkan era serba cepat dengan judul berita yang bombastis dan tendensius.
Nampaknya yang meningkat pesat baru kemampuan menelan mentah-mentah, tanpa mencerna apakah yang ditelannya termasuk data, informasi, opini atau informasi bohong (hoax), keburu diaminkan kemudian disebarkan. Mencerna sesuatu tidak butuh kecepatan tapi kesabaran, kejernihan dan ketepatan dalam memverifikasi data dan informasi.
Masyarakat yang kini juga bisa menjadi pewarta baik dengan mewartakan sendiri atau dengan ikut menyebarkan berita, harus cerdas dengan tidak menganggap ‘delay’ atau penundaan sebagai bentuk kebodohan karena dianggap telat mikir atau tidak kekinian, tapi sebagai kearifan.
Selamat hari pers nasional, 9 Februari 2016.