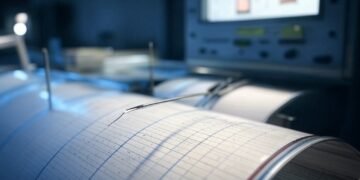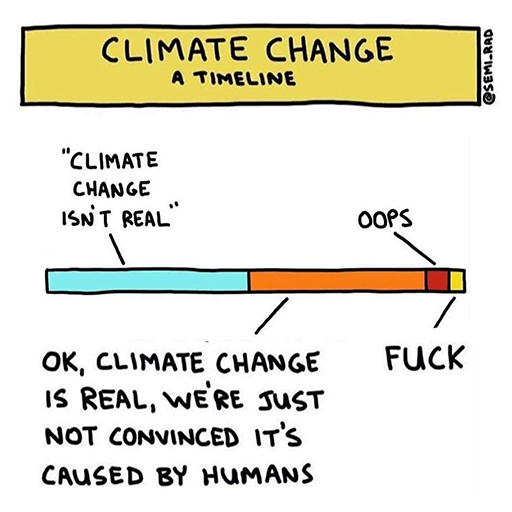Saat mana angin tak berhembus, saat mana dingin tak menembus. Seorang anak kecil berjalan dengan bunga di tangan.
Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Gerangan siapakah ia. Mungkin nama memang tak ia punya. Anak kecil itu berjalan memasuki sebuah negeri yang penuh huru-hara. Negeri yang porak-poranda dilanda bencana.
Sambil berjalan, terdengar ia seperti berbisik. Mungkin ia bernyanyi. Suaranya lirih, tapi tak ada yang peduli.
duh, aduh
nestapa ini dimana ujungnya
pilu ini dimana akhirnya
duh, aduh
duka yang meremukkan jiwa
sajak mana mampu menampungnya
Tanpa letih ia berjalan. Kepada setiap orang yang dijumpainya, ia bertanya. “Maukah engkau menanam bungaku ini. Lihatlah, sebentar lagi ia akan layu.”
Dan seperti biasa, bahkan sudah terlalu wajar jika orang-orang di negeri itu tak ingin ambil peduli. Orang-orang di negeri itu terlalu sibuk dengan urusan-urusan besar. Mereka tak mau dipusingi dengan hal-hal kecil. Hal remeh. Hal sepele. Segala yang tak masuk daftar rencana tentu hanya akan membuang-buang waktu belaka, pikir mereka.
***
Saat mana angin tak berhembus, saat mana dingin tak menembus. Seorang anak kecil berjalan dengan setangkai kembang mawar di tangannya. Terus ia berjalan dan bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Kemudian berjalan lagi. Kemudian bertanya lagi.
Maka masuklah ia ke dalam barisan demonstran dan bertanya, “Tidakkah kalian ingin menanam bungaku ini. Lihatlah, sebentar lagi ia akan layu.” Mereka tidak peduli. Mereka malah kian larut dalam riuh rendah suara mereka sendiri yang memenuhi udara.
Maka bergabunglah ia dalam perjamuan seniman dan bertanya, “Tidakkah kalian ingin menanam bunga ini. Lihatlah, sebentar lagi ia akan layu.” Mereka tidak peduli. Mereka kian larut dalam riuh rendah suara mereka sendiri yang memenuhi udara.
Maka mendekatlah ia kepada para cendekiawan dan bertanya, “Tidakkah kalian ingin menanam bunga ini. Lihatlah, sebentar lagi ia akan layu.” Mereka tidak peduli. Mereka kian larut dalam riuh rendah suara mereka sendiri yang memenuhi udara.
***
Anak kecil dengan setangkai kembang mawar itu kini telah meninggalkan para demonstran. Meninggalkan para seniman. Meninggalkan para cendekiawan. Meninggalkan para begawan. Meninggalkan semua kepura-puraan dan kebodohan.
Berjalan ia dan terus berjalan. Melewati musim demi musim. Badai demi badai. Pusar-pusar angin. Angin mengusung badai. Badai di dalam angin.
Berjalan ia melewati ribuan kisah. Jutaan amarah, sengketa dan prahara. Melewati bangsa-bangsa dan peradaban yang beranjak punah.
Tak ada yang tahu siapa ia. Mungkin nama tak ia punya. Atau tak perlu punya nama. Anak kecil dengan setangkai kembang mawar di tangannya itu pun telah menjenguk mimbar-mimbar orang suci dan bertanya kepada mereka, “Tuan, tidakkah Tuan ingin menanam bunga ini. Lihatlah, sebentar lagi ia akan layu.” Tapi dengan wajah angkuh, mereka malah mengusirnya. “Pergi kau. Wajahmu menunjukkan bahwa engkau pasti bukan dari golongan kami!”
duh, aduh
apa arti semua ini
yang kujumpa hanya
manusia-manusia dungu
membatu hatinya sampai mati
Anak kecil dengan setangkai kembang mawar itu terus berjalan. Saat mana angin tak berhembus, saat mana dingin tak menembus.
Kemudian ia berjalan ke arahmu dan bertanya, “Sudikah engkau menanam bungaku ini. Lihatlah, ayo lihatlah! sebentar lagi ia akan layu.”
Anak itu tersenyum kepadamu. Kau tersenyum kepada anak itu. Hanya saja, kau tak beranjak sedikitpun meraih bunga di tangannya.
(Muhary Wahyu Nurba)