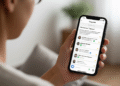Samosir, Sumatera Utara – Matahari di Samosir, Oktober 2025, seolah tak lagi ramah. Sinarnya bukan lagi kehangatan yang menumbuhkan, melainkan bara yang menghanguskan. Di tengah hamparan sawah yang seharusnya hijau dan subur, kini terhampar gurun mini yang memilukan. Retakan-retakan tanah bagai luka menganga, menelan harapan ratusan petani, termasuk Pak Surya.
Bagi Pak Surya, seorang petani paruh baya dengan kulit yang telah digariskan oleh terik matahari dan kerja keras, petak-petak sawah itu adalah segalanya. Itu adalah warisan leluhur, sumber kehidupan, dan jaminan masa depan bagi keluarganya. Namun, di penghujung tahun 2025, kekeringan dahsyat telah merenggut semuanya. “Rp50 juta, bukan sekadar angka bagi saya, Nak,” ujar Pak Surya dengan suara serak, pandangannya nanar menatap sawahnya yang kini tak lebih dari kuburan bagi benih-benih padi yang tak sempat tumbuh. “Itu modal tanam, biaya hidup, dan impian panen yang kini hancur lebur.”
Kisah pilu Pak Surya hanyalah satu dari 210 keluarga petani di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang menjadi korban langsung dari amukan kekeringan ekstrem ini. Selama dua bulan, Oktober hingga November 2025, 14 desa di Samosir berubah drastis. Sungai-sungai yang dulunya mengalir deras, kini hanya menyisakan kerikil dan lumpur kering. Irigasi yang diharapkan mampu mengairi sawah, gagal total. Panen yang dinanti-nanti pun musnah, digantikan oleh keputusasaan yang mendalam.
Situasi ini bukan sekadar bencana lokal. Sumatera Utara adalah salah satu lumbung pangan nasional, menyumbang sekitar 10% produksi beras Indonesia. Ketika Samosir menjerit, ancaman pangan nasional pun mulai menggerogoti. Pertanyaan besar menggantung di udara: apa yang terjadi, dan mengapa ini bisa separah ini?
Penyebabnya bukan rahasia lagi: perubahan iklim ekstrem. Fenomena El Niño yang berkepanjangan telah menyebabkan curah hujan minim sejak September. “Hujan terakhir turun di bulan September,” kenang seorang warga. “Setelah itu, bumi ini haus. Kami menunggu, tapi yang datang hanya terik matahari yang tak henti.” Sungai-sungai mulai mengering di bulan Oktober, dan pada November, kondisi kritis tak terhindarkan. Banyak petani yang terpaksa mencari pekerjaan serabutan di kota, meninggalkan desa dan sawah yang tak lagi menjanjikan.
Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memang tidak tinggal diam. Bantuan berupa truk-truk air bersih mulai didatangkan pada bulan November. Namun, bagi sebagian besar warga, bantuan itu terasa terlambat. “Air datang, tapi sawah kami sudah mati,” keluh warga lain. Video antrean panjang warga yang berebut air bersih, dengan ember dan jerigen di tangan, viral di media sosial. Pemandangan itu memicu gelombang simpati dan solidaritas dari seluruh penjuru negeri.
Donasi pun mengalir deras. Dalam waktu singkat, lebih dari Rp1 miliar terkumpul, menunjukkan bahwa di tengah bencana, masih ada harapan yang tumbuh dari kepedulian sesama. Namun, uang dan air bersih saja tidak cukup untuk mengembalikan lahan yang kering kerontang dan semangat petani yang terkikis.
Pemerintah berjanji akan membangun dan memodernisasi sistem irigasi di Samosir. Sebuah janji yang terdengar seperti oase di tengah gurun, namun petani menuntut lebih dari sekadar janji. Mereka menginginkan aksi cepat dan konkret, solusi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi kekeringan, tetapi juga mengantisipasi ancaman iklim di masa depan.
Tahun 2025 menjadi pengingat yang menyakitkan: perubahan iklim tak pandang bulu. Ia menyerang siapa saja, dari petani kecil di pelosok Samosir hingga ketahanan pangan sebuah bangsa. Kisah kekeringan di Sumatera Utara ini bukan hanya tentang sawah yang retak atau panen yang gagal, melainkan tentang adaptasi, resiliensi, dan pentingnya tindakan nyata sebelum bencana menggerogoti lebih dalam lagi. Ini adalah panggilan untuk bertindak, sebelum Samosir dan daerah lain kembali menjerit.